Book Title : At The Sign Of The Sugared Plum (Sign of the Sugared Plum #1)
Author : Mary Hooper (2003)
Publisher : Bloomsbury
Edition : July 2010, 2nd printing, 169 pages
ISBN : 978 1 4088 1371 3
Di hari yang panas tanggal 7 Juni 1665, Hannah datang ke London untuk menemani kakaknya, Sarah, yang telah lebih dahulu merintis usaha membuat manisan di kota itu. Hannah begitu bersemangat ingin menjadi ‘gadis kota’ yang cantik dan trendi, seperti sahabatnya di desa Chertsey, Abby (Abigail). Setelah menyusuri jalanan London menuju tempat kakaknya di Sugared Plum, dia tidak mendapatkan sambutan yang diharapkannya, karena ternyata sedang terjadi wabah penyakit di London.
Mustahil untuk kembali, Hannah pun tetap dengan rencana semula membantu membuat manisan yang laris di kalangan atas kota London. Wabah masih jauh dari tempat mereka tinggal, sehingga Hannah mulai menikmati hidupnya, melihat bagaimana kalangan atas bergaya, membuat manisan dari berbagai tumbuh-tumbuhan, sampai bertemu dengan Tom, ahli obat magang di tempat Doctor da Silva, yang menarik hatinya.
Tidak lama kemudian, hal yang ditakutkan terjadi, penyakit mulai memakan korban di lingkungan tempat tinggal mereka. Hanya orang-orang kaya yang mampu membuat Sertifikat Kesehatan dan keluar dari London. Orang-orang biasa seperti Hannah dan Sarah hanya bisa pasrah dengan keadaan, mengupayakan pencegahan semaksimal yang mereka bisa di tengah pemandangan mengerikan yang mereka saksikan. Orang-orang saling menghindari satu sama lain agar tidak tertular, satu per satu menjadi ‘gila’ karena rasa sakit dan kematian menyakitkan yang mereka saksikan di depan mata, mayat-mayat yang semakin lama semakin menumpuk hingga tak bisa diperlakukan secara manusiawi, serta usaha-usaha yang terpaksa tutup karena sudah tak ada lagi orang yang mampu membelinya.
Saat membaca buku ini, saya langsung teringat dengan buku The Great Trouble yang mengangkat tema serupa (dan merupakan salah satu favorit saya). Perbedaannya pada setting waktu, di buku ini terjadi dua abad lebih awal, dan wabah yang dimaksud adalah Bubonic Plague (penyakit pes) yang menimbulkan Black Death. Sedangkan di The Great Trouble, terjadi Blue Death akibat penyakit kolera yang terjadi pada abad ke-19. Sudut pandang yang diambil juga berbeda, pada buku ini, Hooper lebih menekankan pada dampak personal dari wabah tersebut, dengan menggunakan sudut pandang orang pertama dari Hannah. Pada The Great Trouble, Deborah Hopkinson memberi gambaran lebih luas mengenai penyakit/wabahnya, sehingga melalui interaksi antar karakternya, kita bisa mengetahui apa penyebab pasti dari wabah, metode penularan, hingga penanggulangannya. Saat ada bagian Hannah mengambil air dari tempat yang lebih jauh dari rumahnya karena di sana ada Abby, saya sempat berpikir akan ada hubungan dengan penyebaran penyakit, termasuk saat rumah majikan Abby membangun sumur sendiri.
Setelah mengalami sendiri wabah yang terjadi pada 2020 yang lalu, rasanya banyak hal yang relate dengan kita saat itu. Covid-19 yang mengisolasi kita dengan lingkungan sekitar, merenggut nyawa orang-orang terdekat kita, mengacaukan rutinitas hidup, dan pengalaman-pengalaman personal lain yang mungkin berbeda-beda satu dengan yang lain. Salah satu yang menjadi pertanyaan saya (karena tidak disebutkan dalam buku ini), apakah pada saat itu, ada juga orang yang denial dan menyepelekan wabah, terutama karena tidak terjadi pada diri mereka, atau karena mereka survive dari penyakit tersebut? Kemungkinan besar tentunya ada, dan mungkin saya perlu menelusuri dari buku nonfiksi terkait (yang sebagian sebetulnya sudah ada di daftar baca).
Kisah Hannah di buku ini diakhiri pada awal September di tahun yang sama, saat sebuah kejadian besar terjadi padanya dan kakaknya. Namun, Bubonic Plague sendiri menurut catatan sejarah baru benar-benar berakhir tahun berikutnya, sekitar waktu terjadinya The Great Fire di London. Kejadian ini tampaknya yang kemudian menjadi setting waktu di sekuel berikutnya. Di catatan belakang buku ini, Mary Hooper menyebutkan beberapa buku yang digunakannya sebagai referensi, di antaranya Pepy’s Diary, The Great Plague of London (W. G. Bell), dan Restoration London (Liza Picard). Dia juga menambahkan beberapa resep manisan yang sangat menarik untuk dicicipi (tetapi perlu upaya untuk membuatnya sendiri).
Buku ini merupakan historical fiction dengan setting abad ke-17 yang sasarannya adalah remaja/dewasa muda (young adult), dengan bumbu romansa secukupnya. Selain mengenai cara bertahan hidup, keluarga, dan persahabatan, ada juga potret mengenai salah satu fase remaja/dewasa awal yang mulai memerhatikan penampilan dan percintaan. Sebagai seorang yang berada di usia dewasa pertengahan, saya tidak terganggu dengan sikap dan perkembangan karakter Hannah, dengan segala kenaifan dan impulsivitasnya. Ketegangan dari buku ini didapatkan karena pembaca tidak bisa tahu siapa ‘korban’ berikutnya, apa yang akan terjadi dengan kehidupan karakter-karakternya.



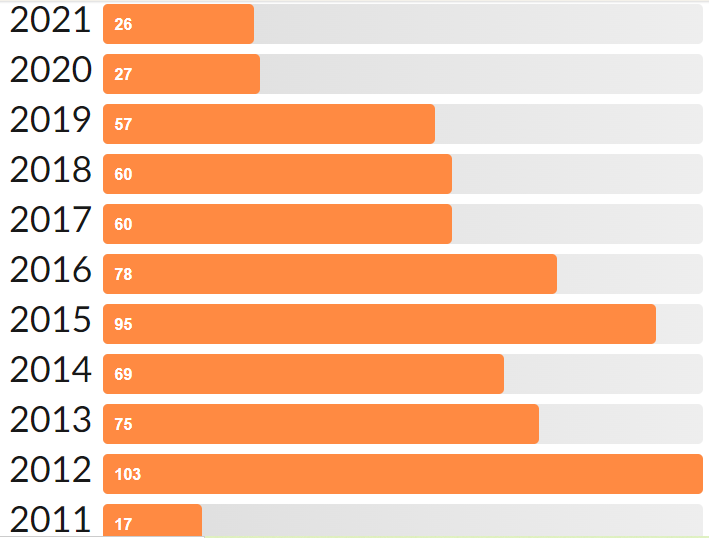


 Judul : Nyanyian Akar Rumput
Judul : Nyanyian Akar Rumput



