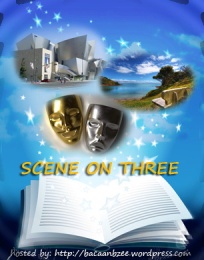Buku yang dibicarakan:
Orkes Madun karya Arifin C. Noer (1999)
Pustaka Firdaus, Cetakan Pertama, Maret 2000, 436 halaman
Topeng Kayu karya Kuntowijoyo
Yayasan Bentang Budaya, Cetakan Pertama, Maret 2001, 258 halaman
Hakim Sarmin Presiden Kita karya Agus Noor
Basabasi, Cetakan Pertama, Maret 2017, 260 halaman
Laki-Laki Bersayap Patah karya Yudhi Herwibowo
BukuKatta, Cetakan Pertama, September 2017, 140 halaman
Ada masanya saya pertama kali membaca karya-karya Shakespeare, naskah drama Oscar Wilde, dan beberapa penulis Eropa yang lain. Dari situ saya memiliki gambaran mengenai play (naskah drama) dari beberapa masa dan gaya. Namun, sebagai orang Indonesia, tentunya tak lengkap jika saya tidak mencicip juga naskah drama karya penulis lokal. Oleh karenanya sejak beberapa tahun lalu, saya pelan-pelan mencari dan membaca naskah drama lokal yang sekiranya bisa memperkaya pengalaman membaca karya jenis ini.
Pada dasarnya, sebuah naskah drama ditulis untuk dipentaskan. Jadi, ketika membaca tulisan-tulisan tersebut, saya memainkan peran-peran di kepala saya. Persamaan dari jenis karya ini, termasuk karya penulis luar negeri, adalah ketiadaan bangunan latar belakang dan karakter yang utuh. Tentunya tidak semua, seperti Vera (Oscar Wilde) yang saya yang rasa cukup kuat karakternya, atau An Ideal Husband yang memiliki konflik yang utuh dan kompleks, ataupun A Doll’s House (Henrik Ibsen) yang menggambarkan setting tempat yang cukup familiar. Namun, tetap kita tidak bisa membandingkannya dengan novel yang memiliki unsur-unsur jelas.
Keempat judul yang saya sebutkan di atas memiliki gaya penulisan dan titik berat yang berbeda, persamaannya adalah, jangan membacanya secara serius, tidak perlu mencari-cari makna di setiap kalimat yang tertulis (atau terucap). Karena seperti yang disebutkan Kuntowijoyo dalam pengantarnya:
 Demikianlah jangan mencoba mencari makna satu per satu dalam drama ini nanti Anda bisa tersesat, tapi cari pesannya. Anggap saja kata-kata itu hanya celoteh yang boleh bermakna boleh tidak. Sebab, seperti kredo puisi Sutardji Calzoum Bachri, kata-kata telah bebas dari makna. Tapi, ada bedanya. Puisi Sutardji Calzoum Bachri memakai mantra sebagai model; jadi yang perlu bukan kata tapi bunyi. Mantra adalah sihir bunyi. Akan tetapi, drama ini lebih dari itu; modelnya ialah dolanan bocah. Dalam dolanan bocah, kata, kalimat, dan bahkan bait semuanya kehilangan makna. Bunyi juga tidak diperlukan. (Topeng Kayu, hal.vi)
Demikianlah jangan mencoba mencari makna satu per satu dalam drama ini nanti Anda bisa tersesat, tapi cari pesannya. Anggap saja kata-kata itu hanya celoteh yang boleh bermakna boleh tidak. Sebab, seperti kredo puisi Sutardji Calzoum Bachri, kata-kata telah bebas dari makna. Tapi, ada bedanya. Puisi Sutardji Calzoum Bachri memakai mantra sebagai model; jadi yang perlu bukan kata tapi bunyi. Mantra adalah sihir bunyi. Akan tetapi, drama ini lebih dari itu; modelnya ialah dolanan bocah. Dalam dolanan bocah, kata, kalimat, dan bahkan bait semuanya kehilangan makna. Bunyi juga tidak diperlukan. (Topeng Kayu, hal.vi)
Meski begitu, ketiga buku yang lain tidak sekental Kuntowijoyo membangun ‘sihir suasana’ seperti dolanan bocah yang diistilahkannya. Orkes Madun sesekali membangun suasana dengan permainan kata tersebut, tetapi dialog antar karakter yang membangun sebuah konflik jauh lebih banyak. Sedangkan Agus Noor lebih mudah ditangkap karena hampir setiap dialognya memiliki makna. Berbeda lagi dengan Yudhi Herwibowo yang banyak menampilkan monolog karakternya, sehingga rasanya kalimat-kalimat di sini menjadi lebih penting dari sekadar pembangun suasana.
Saya tak hendak mengunggulkan karya yang satu dengan yang lainnya, karena memang bukan ahlinya. Namun, dari kacamata sebagai pembaca, saya lebih mudah menikmati Hakim Sarmin Presiden Kita. Buku ini sebenarnya terdiri dari dua buah drama, yaitu Hakim Sarmin dan Presiden Kita Tercinta. Keduanya bisa berdiri sendiri meski sebagian karakternya sama, dan kisahnya berhubungan. Drama ini mengangkat tema mengenai intrik politik, kekuasaan, dan penegakan hukum. Suasana yang digambarkan adalah situasi terkini, penuh dengan sindiran serta referensi politik dan sejarah, dan tentu saja humor yang jamak menjadi bungkus yang relatif aman bagi kritikan terhadap penguasa, sekaligus menghibur pembaca (atau penonton).
 Sebab hakim yang gila hanya mungkin dilahirkan oleh masyarakat yang gila. Hukum itu cermin masyarakat, kalau hakimnya gila, pasti masyarakatnya lebih gila. (Hakim Sarmin, hal.52)
Sebab hakim yang gila hanya mungkin dilahirkan oleh masyarakat yang gila. Hukum itu cermin masyarakat, kalau hakimnya gila, pasti masyarakatnya lebih gila. (Hakim Sarmin, hal.52)
Kita memang hidup di zaman yang telah dipenuhi kegilaan. Keadilan dan kegilaan sulit dibedakan. (Hakim Sarmin, hal.122)
Revolusi selalu dimulai oleh mereka yang gila… (Hakim Sarmin, hal.128)
Hakim Sarmin sendiri menitikberatkan pada pergerakan revolusi hukum dan kekuasaan, dengan plot twist yang bertebaran di mana-mana. Sedangkan Presiden Kita Tercinta menceritakan tirani dan kudeta dari sudut pandang pemilik kekuasaan. Dari bayangan saya, untuk mementaskan lakon ini cukup mudah, karena disertai panduan dari penulisnya sendiri, dan propertinya tidak terlalu rumit. Namun, oleh karena situasinya sangat terkini, dengan bahasa dan istilah kekinian tersebar dalam kalimat-kalimatnya, rasanya jika suatu saat buku ini menjadi klasik, akan memerlukan catatan kaki untuk menjelaskan kata dan istilah tersebut.
Menawi Diparani,
….
Demokrasi hanyalah jalan. Dan kita tahu, banyak jalan menuju Roma.
Paringan,
Jangan lupa pake Wise atau GPS… biar tak tersesat…
Pak Kunjaran,
Setuju!
(Hakim Sarmin, hal.117-118)
Orkes Madun dimaksudkan menjadi sebuah pentalogi, tapi lakon kelima, Magma, belum sempat ditulis. Namun, karena penulis sudah bercerita ke mana-mana mengenai Magma, anak-anak Sekolah Perancis di Jakarta yang juga mendengar kisahnya membuatnya menjadi komik dan dimuat dalam buku ini. Keempat lakon yang telah ditulis dan dipentaskan di Teater Kecil berturut-turut; I. Madekur dan Tarkeni, IIa. Umang-Umang, IIb. Sandek, Pemuda Pekerja, dan IV. Ozone.
Tema yang diusung dalam keempat lakon ini cukup luas, dan ada keterkaitan satu sama lain. Tentang kemiskinan, kekuasaan, gender, nafsu manusia, yang disampaikan seolah tanpa beban. Bahkan ada beberapa detail sains yang sangat relevan meski disebutkan sambil lalu. Banyak di antara kalimat-kalimat karakternya yang spontan dan acuh, terselip sindiran, kebijaksanaan, maupun celetukan yang cukup filosofis.
 …kapitalis tetap akan memegang tampuk pemerintahan di mana-mana. Barangkali dan bukan tidak mungkin kapitalis akan meminjam nama lain, bahkan bukan mustahil ia akan tampil sebagai seorang komunis atau seorang sosialis. (Sandek, hal.254)
…kapitalis tetap akan memegang tampuk pemerintahan di mana-mana. Barangkali dan bukan tidak mungkin kapitalis akan meminjam nama lain, bahkan bukan mustahil ia akan tampil sebagai seorang komunis atau seorang sosialis. (Sandek, hal.254)
BOROK : Hukuman apa yang paling hebat di dunia selain hukuman mati? Saya rela dipancung. Saya sudi ditembak berkali-kali. Saya mau dicincang-cincang lalu dicampur dengan adonan semen. Saya mau mati.
RANGGONG : Justru sebaliknya. Hukuman yang paling berat ternyata adalah menanggung kehidupan dan hidup lebih dari kemampuan kita. Hukuman hidup!
(Ozone, hal.321)
 Laki-Laki Bersayap Patah juga merupakan kumpulan drama, yaitu Aku, Aku; Laki-Laki Bersayap Patah; Terkutuk; dan Pendekar Sesat, Pendekar Ular. Jika dibandingkan dengan drama lain yang disebutkan di sini, dialog serta konflik dalam buku ini lebih ‘serius’. Hampir setiap kalimatnya bermakna, tidak didominasi dengan kata-kata ‘sihir suasana’. Drama yang diangkat lebih menitikberatkan pada konfliknya, sehingga plot yang disuguhkan menyimpan kejutan penyelesaian di akhirnya yang menanti memberi kejutan. Temanya pun menarik, yang cukup terasa adalah konflik psikologis dan drama keluarga yang cukup gelap.
Laki-Laki Bersayap Patah juga merupakan kumpulan drama, yaitu Aku, Aku; Laki-Laki Bersayap Patah; Terkutuk; dan Pendekar Sesat, Pendekar Ular. Jika dibandingkan dengan drama lain yang disebutkan di sini, dialog serta konflik dalam buku ini lebih ‘serius’. Hampir setiap kalimatnya bermakna, tidak didominasi dengan kata-kata ‘sihir suasana’. Drama yang diangkat lebih menitikberatkan pada konfliknya, sehingga plot yang disuguhkan menyimpan kejutan penyelesaian di akhirnya yang menanti memberi kejutan. Temanya pun menarik, yang cukup terasa adalah konflik psikologis dan drama keluarga yang cukup gelap.
Ada aroma surealisme yang kental dalam drama-drama di buku ini, yang membuat saya seolah membaca cerpen. Ternyata memang ada lakon yang diubah bentuk dari cerpen penulisnya sendiri. Dengan membaca dalam bentuk drama (atau menontonnya), rasanya mungkin akan lebih mudah dibayangkan. Begitu pula karakternya, masing-masing memiliki pembeda yang menonjol, sehingga akan lebih membutuhkan pendalaman bagi para pemeran untuk menampilkannya. Apalagi di sini banyak sekali monolog, baik itu percakapan batin, maupun penjelasan situasi yang disampaikan secara panjang lebar. Di satu sisi kita mengetahui lebih dalam mengenai konflik dan karakternya, tetapi di sisi lain monolog ini semacam kurang memaksimalkan interaksi antar karakter yang seharusnya membangun sebuah drama.
Dalam Topeng Kayu, Kuntowijoyo hendak mengkritisi kekuasaan, semua kekuasaan selain kekuasaan Tuhan (hal ini disampaikannya dalam pengantar). Rasanya memang pengantar ini menjadi sangat penting bagi pembaca awam seperti saya, yang hanya bisa menangkap sedikit-sedikit dari sihir suasana yang dibangun begitu kokoh.
Tanpa impian kenyataan tak terasa. Tanpa larangan kebolehan tak terasa. Tanpa ikatan kemerdekaan tak terasa. Tanpa kejahatan kebaikan tak terasa. Tanpa hitam putih tak terasa. Ternyata kita tersesat! (Topeng Kayu, hal.120)
Wah, itulah kesalahan umum. Disangka segalanya berhubungan. Tidak selalu harus. Perbuatan tidak selalu harus berhubungan dengan hasilnya. Pohon tidak selalu berhubungan dengan buahnya. Itu mesin. Itu nalar. Itu pikiran. Kekuasaan yang sempurna di luar semua itu. (hal.219)
Dari keempat buku yang saya baca ini, rasanya masih penasaran dengan karya yang lain, dan utamanya, masih ingin melihat karya-karya ini dipentaskan. Apakah bisa semakin menjelaskan maksudnya, atau justru menimbulkan kesan yang baru?
 Judul : Empat Aku: Sekumpulan Kisah
Judul : Empat Aku: Sekumpulan Kisah



 Laki-Laki Bersayap Patah juga merupakan kumpulan drama, yaitu Aku, Aku; Laki-Laki Bersayap Patah; Terkutuk; dan Pendekar Sesat, Pendekar Ular. Jika dibandingkan dengan drama lain yang disebutkan di sini, dialog serta konflik dalam buku ini lebih ‘serius’. Hampir setiap kalimatnya bermakna, tidak didominasi dengan kata-kata ‘sihir suasana’. Drama yang diangkat lebih menitikberatkan pada konfliknya, sehingga plot yang disuguhkan menyimpan kejutan penyelesaian di akhirnya yang menanti memberi kejutan. Temanya pun menarik, yang cukup terasa adalah konflik psikologis dan drama keluarga yang cukup gelap.
Laki-Laki Bersayap Patah juga merupakan kumpulan drama, yaitu Aku, Aku; Laki-Laki Bersayap Patah; Terkutuk; dan Pendekar Sesat, Pendekar Ular. Jika dibandingkan dengan drama lain yang disebutkan di sini, dialog serta konflik dalam buku ini lebih ‘serius’. Hampir setiap kalimatnya bermakna, tidak didominasi dengan kata-kata ‘sihir suasana’. Drama yang diangkat lebih menitikberatkan pada konfliknya, sehingga plot yang disuguhkan menyimpan kejutan penyelesaian di akhirnya yang menanti memberi kejutan. Temanya pun menarik, yang cukup terasa adalah konflik psikologis dan drama keluarga yang cukup gelap.



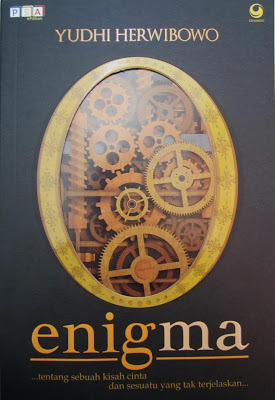 Judul : Enigma
Judul : Enigma